 |
| sumber: lontarmadura.com |
Menyelami kehidupan masyarakat Madura dari masa ke
masa akan menemukan sejumlah kearifan dalam berbagai bentuk tradisi, adat dan
kebudayaan, meskipun sudah mulai tertimbun oleh gemerlap kehidupan yang serba
materialistik. Masyarakat bukan hanya kumpulan orang-orang dengan segala wujud
benda-benda yang dihasilkannya. Masyarakat adalah sumber nilai-nilai yang
terlembagakan dalam berbagai norma kebiasaan dan hukum sosial yang mengakar dan
berkesinambungan.
Terlepas dari ketetapan universal bahwa perubahan
adalah sebuah keniscayaan, keberadaan sebuah tradisi tetap menjadi acuan
kearifan yang senantiasa menuntut perhatian dan tagihan-tagihan primordial
untuk terus dilestarikan. Berperang melawan dinamika sosial masyarakat modern,
tradisi dapat digunakan sebagai senjata dalam menangkis dan menyerang sekaligus
isme-isme yang bertolak belakang dengan kultur lokal kemaduraan.
Sangat ironi dan gegabah, bila pembaruan dan
kemajuan disyaratkan harus menolak tradisi, sebagaimana juga terjadi pada
gerakan puritanisasi Islam yang dipahami sebagai upaya penghapusan tradisi
masyarakat, yang terus mempertentangkan antara fenomena historis dan doktrin
normatif. Padahal, tradisi adalah rumah, yang menjadi tempat pulang, tinggal
dan berkarya membangun masa depan yang lebih baik. Layaknya sebuah rumah,
tradisi butuh perawatan dan modifikasi sesuai kondisi yang ada, dan jangan
terlalu lama ditinggalkan, agar ia tidak roboh sebelum mampu membangun rumah
yang baru. Salah satu tradisi yang sangat membutuhkan sentuhan perawatan dan
pembaharuan adalah tradisi pangantan Madura.
Pangantan Madura, sebagai
sebuah tradisi yang sudah melembaga di lintas ruang dan waktu, meskipun sudah
mulai luntur dari warna aslinya, menyimpan serumpun makna sosial dan ajaran
filsafat rumah tangga yang sangat luhur, selain mengandung daya seni yang
menghibur. Oleh karena itu, membiarkan tradisi pangantan Madura dalam
keadaannya yang sekarang (baca: tersisih dan terserat oleh “glamorisme”),
merupakan sikap apatis yang haram, dan berimplikasi pada runtuhnya sendi-sendi
moralitas kemaduraan.
Pangantan Masa Silam Vs Masa Kelam
Prosesi pangantan Madura, memiliki
bagian-bagin tersendiri yang unik di setiap tempat, walaupun punya benang merah
yang mengikat secara universal. Sebab itulah, tulisan ini tidak bermaksud
membatasi tradisi pangantan Madura, tetapi sekedar menginformasikan dan
mengkaji beberapa sisi sesuai dengan sudut pandang dan pengalaman penulis.
Kemungkinan terjadi perbedaan-perbedaan sangat besar, justru inilah wujud
kreativitas para leluhur orang Madura, terutama mereka yang menjadi kreator
budaya, dengan menyelipkan berbagai nilai-nilai dan kearifan yang tak
terhingga.
Bermula dari ingatan di masa kecil dan hasil informasi
dari beberapa sesepuh, secara umum tradisi pangantan Madura di masa
silam, menjadi ajang mengolah ilmu dan kedigdayaan yang sangat dalam dan penuh
kesantunan. Kedua hal tersebut sama-sama ditunjukkan oleh para perwakilan kedua
mempelai, sesuai dengan jumlah rombongan masing-masing. Setiap rombongan
mempunyai posisi dan tugas yang berbeda sehingga tertata dengan rapi, tidak
seperti tradisi pengantin Madura yang berkembang dewasa ini.
Rombongan pangantan Madura terdiri dari
beberapa kelompok yang membentuk garis memanjang (horizontal), dari paling
depan sampai paling belakang. Kelompok paling depan adalah para anak-anak
perempuan usia belasan tahun dengan pakaian ala kedaton, berperan sebagai
dayang, yang berjumlah delapan sampai dua belas orang, sambil membawa berbagai
jenis kue, biasa disebut dengan kelompok patampa, berasal dari bahasa
Madura, nampa. Jumlahnya tidak boleh ganjil, karena mereka harus
berjalan berpasangan satu sama lain, dengan jajan yang etampa e tanang,
sampai rumah tujuan.
Kelompok kedua, berada di baris kedua, adalah para
sesepuh yang memiliki kapasitas mumpuni di bidang sastra dan budaya Madura,
dengan pakaian resmi sesuai adat tinggi Madura, yang berjumlah sebanyak enam
sampai dua belas orang (harus genap), berjalan beriringan dengan penuh sopan
santun, biasa disebut pangereng, berasal dari bahasa Madura, ngereng.
Tugas para pangereng adalah melakukan serah terima dengan bahasa Madura
tinggkat tinggi, baik strata maupun sastranya, baik dalam bentuk ceramah, papparegan
ataupun tembang, yang saling berbalas-balasan.
Kelompok ketiga, terdiri pangantan lake’
sebagai pangantin utama, dengan pengantin-pengantin lain (pengantin
pendamping), yang terdiri dari kerabat dekat, lengkap dengan kelompok pembawa
dan penabuh musik saronen selaku pengiring kenca’na jaran yang
ditunggangi oleh para pengantin. Ini didasarkan pada kebiasaan bahwa
iring-iringan pengantin dimulai dari rumah pangantan lake’, untuk
menjemput pangantan bini’. Kemudian secara bersama-sama (pangantan
lake’ ban bini’) beriringan kembali ke rumah pangantan lake’ sebagai
bentuk balasan.
Di barisan paling akhir, biasa terdiri dari
orang-orang yang ikut nimbrung mengiri pengantin, baik anak-anak ataupun orang
tua, laki-laki atau perempuan, berjalan kaki atau naik sepeda, yang secara suka
rela menjadi partisipan dalam rangka semakin memeriahkan tradisi pangantan
tersebut. Suara teriakan dan tawa mereka bercampur baur dengan lantunan bunyi
saronen. Kemeriahan ini ditambah dengan orang-orang yang meskipun tidak ikut
mengiring, tapi sengaja ngamba’ (menunggu) di pinggiran jalan yang
menjadi jalur lintasan rombongan pangantan. Mereka berjibaku merebut
tempat terdepan dengan penuh senyum dan tawa lebar yang sesekali melambai tagan
pada pangantan yang melenggok di atas kuda sesuai iringan saronen.
Begitulah sekilas struktur komponen pangantan
Madura di masa silam, yang jelas sangat berbeda dengan pangantan masa
sekarang yang sudah mulai kelam. Meskipun sama-sama pangantan jaran
(pengantin kuda), kelompok patampa dan pangereng sudah mulai
tidak dipakai dan cukup hanya dengan sekelompok pengantin dan penabuh saronen.
Itupun tidak tertata rapi seperti dahulu dan lebih mementingkan kualitas kuda
dengan kenca’na yang apik dan group saronen dengan dandanannya yang
menor, dari pada adat kemaduraan yang dilandasi pertimbangan etis dan estetis.
Lebih jauh lagi,
munculnya pangantan koadi (pengantin di atas pelaminan) semakin menambah
runyam persoalan dan merusak beberapa tradisi yang sudah mengakar cukup lama. Saronen
sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan orkes dangdut dan pagelaran seni
tayub yang semakin tidak jelas moralitas keseniaanya. Tembang-tembang kasmaran,
aratate dan senom yang biasa dilantukan oleh para pangereng
pangantan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang berisi falsafah
dan ajaran hidup berumah tangga, diganti dengan kejung-kejung murahan
dan temangan yang tidak jelas arahnya.









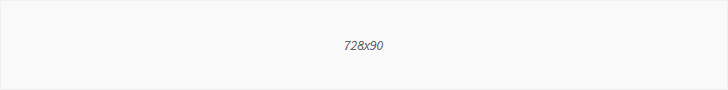







Tidak ada komentar:
Posting Komentar