Pak Sukimin
bukan orang kaya, tapi beliau punya cita-cita mulia: naik haji. Maka ia bekerja
keras, siang malam, sampai kadang lupa istri anak cucu. Di tengah perjalanan
umurnya yang semakin senja, ia berlomba dengan ajal: jangan sampai aku mati
sebelum naik haji. Apalagi setelah pulang dari pengajian umum kemarin malam,
niatnya semakin mantap: kata pak kiai tidak ada balasan bagi haji mabrur
kecuali surga. Lho, jangan heran, siapa yang tak kepincut dengan segala
kenikmatan surga?
“Pak, apa
tidak sebaiknya uang yang sampean simpan tuk naik haji digunakan untuk biaya
pendidikan anak cucu kita?” Suatu sore, selesai shalat Maghrib, istrinya
memberikan usul. Jelas saja pak Sukimin sewot. Haji lebih penting dari sekolah
anak cucunya. Bahkan lebih penting dari hidup seluruh keluarganya, yang sedikit
kekurangan.
Tidak masalah
hidup miskin asalkan bisa naik haji. Tuhan menanggung riski semua mahklukNya,
apalagi makhlukNya yang sudah berhaji. Nasib anak istri langsung dipasrahkan
kepada Tuhan. Dan Tuhan Yang Maha Penyayang, tentu akan sangat senang. Itulah
yang membuat pak Sukimin terus bersikukuh: tak perlu mendengar ocehan istri dan
anak-anaknya. Sepetak sawah dan dua ekor sapi peliharaannya, sudah dijual untuk
membayar ONH.
Pak Sukimin
hidup di sebuah kampung yang sangat religus: kiai yang memimpin kampung ini,
setiap tahun selalu berhaji, kebetulan beliau punya KBIH. Hampir di setiap
kesempatan, di acara pengajian maupun kompolan, sang kiai tak pernah
bosan untuk selalu memberikan wejangan bahwa tiada kesempurnaan bagi seseorang
yang belum menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji. Pernah ada salah satu
anggota jama’ah, kebetulan seorang pelajar di sebuah madrasah aliyah di kampung
tersebut, yang mangkir dari latihan manasik karena dia ikut ujian di sekolah,
seketika sang kiai marah-marah: latihan manasik ini lebih penting dari
sekolahmu! Seolah haji adalah ibadah paling sulit yang tidak akan sah kalau
tidak ikut dan melalui latihan-latihan di KBIH.
Sementara di
sisi lain, penduduk kampung ini rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Ada
sebagian yang terbilang cukup kaya, tapi di antara mereka tidak terjalin
hubungan yang berkeadilan. Kepedulian terhadap orang-orang kecil, yang
barangkali sampai seumur hidupnya tidak akan akan punya kesempatan untuk
berhaji, yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama, malah kurang mendapat
ruang yang wajar. harta yang sudah dikumpulkan dan diniatkan untuk berhaji,
tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain, termasuk kepentingan untuk membantu
tetangga yang miskin. Menunda, apalagi menggagalkan niat berhaji adalah sebuah
dosa, katanya.
Haji
dan Ambisi Duniawi
Di Madura,
sebagaimana yang saya tahu, salah satu tradisi para jama’ah haji sebelum
kembali ke rumah nilai norma budayanya masing-masing: mereka mengganti nama.
Hal tersebut seandainya memungkinkan akan dilanjutkan dengan ganti KTP dan
Kartu Keluarga, kalau perlu Akta Kelahiran. Jangan panggil Sukimin lagi, tapi
H. Khairul Basyar. Atau minimal pak, om, kek, mbah Haji, sebagai sebutan
kehormatan. Kopyah hitam berubah putih, plus surban melilit di leher. Bahkan
cara berjalan juga ikut berubah, keramahan pada tetangga sedikit ditekan.
Langkah lebih percaya diri.
Kita bukan
tidak tahu, atau barang kali banyak yang lupa, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman
dan Ali, juga para sahabat Rasulullah yang lain tidak pernah menambah huruf “H”
di depan namanya setelah mereka naik haji. Mereka hati-hati: jangan sampai
riya’ bin sum’ah, nanti kemabruran hajinya batal. Atimmul hajja wal ‘umrota
lillah! Ah, soal itu kan urusan hati, tidak ada kaitannya dengan memakai
peci putih dan panggilan pak haji. Ini Madura lho, punya tradisi dan kebudayaan
yang berbeda. Memang iya, tapi kalau hajimu itu hanya sekedar rekreasi untuk
meraih gengsi lebih tinggi, orang-orang di sekitarmu akan mengolok-olok kamu
dengan sebutan “jitasbani”: e attas ajji, e baba banni. Sebuah
sebutan untuk haji mardud, haji yang ditolak.
Naik haji itu
wajib dalam hukum Islam. Adalah benar orang yang berjuang keras untuk bisa
menunaikannya. Namun persolannya, di tengah kemelut kemiskinan masyarakat kita:
layakkah kita berhaji dengan mengesampingkan mereka yang miskin, dan yatim
secara nasab maupun sosial? Jawabannya tergantung sejauh mana kita memahami
agama terakhir ini. Berhajilah, tapi selesaikan dulu tanggung jawab sosialmu.
Jangan sampai ibadah yang kita lakukan dijadikan sebagai pelarian tanggung
jawab kita kepada para kaum lemah. Atau sekedar manipulasi religiusitas yang
pada hakikatnya justru melanggar nilai esensial haji itu sendiri.
Haji
dan Kewajiban Sosial
Saya pikir
Sukimin di Madura, tidak hanya satu: banyak. Mugkin ada di setiap daerah. Orang
yang pikirannya sederhana: seolah dengan nekat naik haji segalanya selesai. Surga
sudah di depan mata. Tinggal santai saja menunggu ajal tiba. Padahal selesai
berhaji, kita dituntut kerja keras, karena kita telah menggondol sebutan “mabrur”
(haji yang diterima) di sisi Allah dalam berhaji.
Kenapa haji
harus mabrur? Ya, jangan pergi haji kalau tidak mau mabrur. Haji
adalah puncak amal, dari serangkaian amal Islam yang dimulai dengan syahadat.
Nilai kemabruran haji ditentukan oleh kualitas rangkaian ritual sebelumnya.
Jangan yang penting dipanggil pak haji, sementara shalatnya hanya berhenti pada
formalitas takbiratul ihram dan salam. Zakat dianggap sempurna dengan hanya
menyerahkan satu gantang makanan pokok pada yang berhak. Puasa ya cukup merubah
kebiasaan makan dan minum saja.
Haji sama
dengan al-qashdu, maksud atau keingian, mabrur berarti al-birru,
kebaikan. Melaksanakan haji berarti melaksanakan keinginan untuk menjadi baik,
minimal mencari kebaikan. Salah satu indikasi kabaikan dalam bahasa al-Quran
adalah mampu menafkahkah sesuatu yang kita cintai untuk kepentingan agama dan
umat. Nafkahkan jabatan yang kita cintai untuk kebaikan bersama, bukan sarana
meraih keuntungan sepihak.
Haji menyimpan
kewajiban sosial. Tangan yang berlumuran minyak rela digunakan untuk membuang
duri dan batu di jalan agar tak mengganggu orang yang lewat. Semakin giat
megang cangkul ke sawah dan ke ladang. Tubuh yang kita sayangi kita nafkahkan
untuk berbuat yang terbaik bagi seluruh alam, tanpa melihat perbedaan personal
dan lokalitasnya.
Kalau kita
berhaji sekedar ingin merubah kopyah hitam ke putih, atau mencari legalitas
memakai surban, ya terserah!
Ares Tengah,
11 Februari 2011









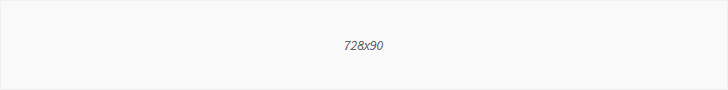








Tidak ada komentar:
Posting Komentar