 |
| sumber: dakwah.web.id |
Di penghujung
tahun pelajaran 2015/2016, adik lelaki saya baru lulus sekolah dasar. Ia
orangnya suka bermain dan terbilang super aktif. Mungkin karena banyak dari
teman sepermainannya, yang juga sama-sama baru lulus, ingin melanjutkan studi
ke pesantren, akhirnya adik saya punya keinginan yang sama. Ia ingin pula
mondok ke pesantren, padahal sebelumnya sangat ngotot mau melanjutkan ke salah
satu SMPN favorit yang cukup jauh dari rumah. Pelan-pelan, orang tua saya
menyukuri atas perubahan keinginan adik saya, yang menurut mereka sungguh di
luar dugaan.
“Carikan
adikmu pesantren yang cocok, tapi kalau bisa jangan terlalu jauh dari rumah!”,
suara ibu lewat telepon pada suatu malam. Belum saya berpikir, tiba-tiba saja
sudah nongol di pikiran sebuah pesantren yang memang sudah lama saya ganderungi:
Ponpes Nasyatul Muta’allimin (Nasa) Mandala Gapura. Dulu saya pernah punya
cita-cita untuk mondok di pesantren ini, tapi karena dorongan kuat orang tua,
saya lalu disuruh mondok di Ponpes Mathali’ul Anwar Pangarangan Sumenep. Empat
tahun di sana, ternyata saya menemukan banyak hal tak terduga yang sangat
bermanfaat bagi kehidupan saya kelak.
Rasa penasaran
akan pesantren Nasa ini tak pernah hilang dari pikiran: meskipun saya sendiri
sudah tidak mungkin punya kesempatan. Selama ini saya hanya berhubungan secara
individual dengan alumni santri di sana, bahkan dengan salah satu putera
terbaik pengasuhnya, kala itu. Mungkin inilah kesempatan untuk semakin erat
menjalin hubungan: adik saya harus mondok di Nasa. Saya pun bicara dengannya
secara baik-baik, awalnya menolak, tapi pada akhirnya ia setuju dengan pilihan
saya, kedua orang tua kami pun ikut merestuinya.
Kurang dari
seminggu dari hari lebaran ketupat, adik saya berangkat ke pesantren. Beberapa
hari menjelang keberangkatan banyak orang-orang, kerabat dan tetangga dekat
yang ketar-ketir: khawatir adik saya tidak kerasan di pesantren. Kami
sekeluarga juga demikian, dengan alasan yang sama: adik saya suka bermain.
Barangkali dia tidak betah dengan aturan dan kebiasaan di pesantren. Tidak
sebagaimana di rumah, semua di pesantren tertata dengan rapi sesuai ketentuan.
Keesokan
harinya, setelah sehari di pesantren, tiba-tiba ada nomor baru nelpon dan
seketika terdengar suara yang tak asing di seberang sana: “Kak, belikan saya
kopyah hitam (songkok nasional), lalu antarkan sekarang ke pesantren!”, saya
agak sedikit heran, dan tak sabar untuk bertanya: “Lho, kopyahnya kan sudah
ada, kok mau beli kopyah lagi?”, adik saya segera menjawab: “Di sini semua
santri ga boleh pakai kopyah selain kopyah hitam!”, saya pun mengerti dan
langsung mengiyakan.
Saya berangkat
membeli songkok hitam dan sekalian mengantarkannya ke pesantren. Sepanjang
jalan, hati dan pikiran diliputi pertanyaan: apa gerangan yang menyebabkan
pesantren melarang santrinya memakai kopyah apapun selain songkok hitam?
Padahal memakai peci putih, peci yang biasa di pakai oleh orang Madura yang
sudah berhaji, dan sejenisnya merupakan model kopyah yang sudah biasa dipakai
para santri, baik saat masih di pesantren atau setelah pulang ke kampung
halaman.
Sampai di
pesantren, saya hanya menyerahkan kopyah yang dimaksud kepada adik saya. Saya
tidak bertanya soal larangan memakai kopyah yang lain. Saya hanya mengamati
situasi sekitar: semua santri memakai kopyah hitam, tidak ada satupun, semua
sama. Saya pun teringat, saat mengantarkan adik saya kemarin, saat bertamu ke
kiai pengasuh sebagai adat serah terima adik saya yang mau mondok, beliau
mengenakan kopyah yang sama: songkok nasional. Ingatan saya juga menampilkan
kenangan selama saya berhubungan adik sang kiai, yang kebetulan cukup akrab
dengan saya, beliau juga hanya mengenakan kopyah hitam, dalam berbagai
kesempatan.
Peci Putih dan
Kopyah Hitam
Lama kelamaan,
setelah berbulan-bulan, saya terus menjalin silaturrahim dengan warga
pesantren, saya baru menemukan alasannya. Pesantren Nasa Mandala Gapura ini
memiliki pertimbangan kebudayaan yang luar biasa. Sebuah pertimbangan yang
terakumulasi dari rajutan nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal yang sangat
seimbang. Maka lahirlah sebuah kebijakan dan aturan pesantren yang berparas
ganda; keluhuran agama dan kearifan budaya.
Aturan memakai
kopyah hitam bagi para santri, bahkan bagi para kiai sekeluarga, merupakan
bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang sudah menunaikan secara sempurna
rukun Islam kelima. Peci putih biasa digunakan sebagai mahkota oleh orang-orang
Madura yang pergi berhaji sepulangnya dari tanah suci. Peci putih adalah
identitas kesucian. Dalam kearifan budaya Madura, orang yang sudah berhaji
harus suci hati dan pikirannya. Perbuatannya harus menjadi teladan bagi yang
lain, dalam bahasa agama disebut haji mabrur. Kalau peci putih justru
melambangkan sebaliknnya, sekedar manipulasi dan kegengsian diri, maka orang-orang
Madura akan menyebutnya “jitasbani”: e attas ajji, e baba banni (di atas
haji, di bawah bukan), alias haji fasiq!
Nasa sebagai
pesantren yang berkearifan, berpandangan bahwa orang yang mengenakan peci putih
dianggap sebagai perbuatan yang cangkolang: melanggar adat kesopanan
terhadap para haji di Madura. Ini yang diwariskan kepada para santri dengan
membuat sebuah kebijakan untuk mengenakan kopyah hitam. Sebelum berhaji, jangan
coba-coba mengenakan peci putih: itu belum pantas dan melanggar kesopanan.
Walaupun tidak dipatenkan sedemikian rupa, sehingga bila saja ada orang yang
ingin menyembunyikan kehajiannya dengan memakai kopyah hitam, atau sebaliknya,
ya silakan. Sebab dalam kebudayaan Madura, selalu ada ruang terbuka untuk
segala perbedaan.
Waktu saya di
pesantren, di Pangarangan Sumenep, maha guru kami, Kiai Abussuyuf Ibnu Abdillah
pernah memberikan wejangan bahwa tata busana orang Madura yang disepakati oleh
para kiai adalah memakai kopyah hitam, baju lengan panjang dan sarungan.
Meskipun namanya “songkok nasional” yang bisa dikenakan oleh siapa saja, tapi
orang-orang Madura menggunakannya sebagai identitas busana mereka (para
lelaki). Memakai pakaian di luar itu, jelas merupakan budaya impor yang sebisa
mungkin perlu dihindari, kecuali pada kasus-kasus tertentu sesuai tuntutan
situasi.
Maka demikian,
pesantren punya peran strategis dan fundamental dalam melestarikan kebudayaan
Madura, terutama pesantren yang masih mempertahankan nuansa tradisionalnya.
Memang sekilas tampak aneh, apabila ada pesantren yang sedari awal merupakan
hasil konstruksi kebudayaan, tiba-tiba ingin keluar dari kebudayaan yang
melahirkannya. Menjadi modern, bukan berarti harus mengganti pakaian dari
sarung ke celana, tetapi merubah pikiran dari kebodohan dan kejumudan menuju
kecerdasan dan pembauran. Tentu dengan tetap berkearifan lokal dan berdaya
saing global.
Ares Tengah,
11 Desember 2016









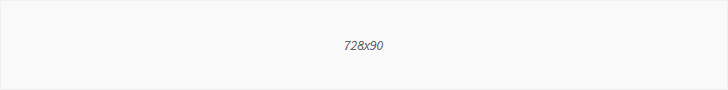







Tidak ada komentar:
Posting Komentar