 |
| sumber: rembang.org |
Suatu malam, saya dengan seorang sahabat, yang
kebetulan sebagai seorang ustadz di sebuah pesantren, ngobrol santai di
pinggir jalan tanpa nama. Dia lulusan sebuah pesantren salaf, mulai dari Madura sampai hijrah
ke tanah Jawa, sahabat saya tetap sama: menekuni pendidikan kitab klasik di
pesantren salaf. Saat kami lagi asyik ngobrol, seketika ada seorang setengah
baya, seorang haji, tokoh masyarakat di kampungnya, memanggil salam lalu
bergabung bersama kami.
“Saya mau bertanya ustadz!” Tentunya ia
bertanya pada sahabat saya. “Saya mau memondokkan anak saya ke pesantren tempat
sampean belajar di Jawa. Tapi,
apakah di sana juga mengeluarkan ijazah?”, dengan mimik muka benar-benar serius.
“Ya, juga mengeluarkan ijazah!”, sahabat saya menjawab singkat. Saya
melihat ada yang lain di wajah pak haji,
dengan dahi sedikit mengkerut.
“Katanya pesantren salaf, kok mengeluarkan
ijazah?”, kembali ia bertanya. Kali ini dengan nada dan ekspresi yang penuh dengan keraguan dan keheranan.
“Lho, salaf itu bukan berarti tidak mengeluarkan
ijazah. Ijazah di sana ijazah lokal, asli pesantren, bukan seperti ijazah
di sekolah umum!”, agak panjang lebar sahabat saya menjawab.
“Tapi saya tetap tidak ingin anak saya mondok di
pesantren yang mengeluarkan ijazah!”,
iapun pergi. Tanpa
salam lagi. Saya melihat jelas: seraut kekecewaan bergelantung di wajahnya.
Sementara saya diam. Ada sesuatu yang timbul tenggelam di pikiran dan hati
saya. Pesantren, salaf dan ijazah, tiga variabel yang meloncat-loncat di ruang
kesadaran.
Apa yang dirisaukan oleh pak haji di atas tentang
ijazah pesantren memang sangat saya maklumi. Orang dusun sepertinya masih
memiliki logika yang polos dan linear. Padahal di luar sana, ada banyak hal
yang mungkin tak terjangkau oleh energi pemikiran, bahkan mungkin oleh
gelombang elektromagnetik imajinasinya. Pesantren yang dulu pernah ia jalani semasa muda, jelas
tidak sana dengan pesantren yang akan harus dijalani oleh anaknya.
Salaf Bukan Pesantren
Dalam logika berpikir pak haji di atas, pesantren
salaf dipahami sebagai sebuah pesantren yang tanpa “ijazah”. Sangat sederhana,
namun juga sedikit rumit. Pesantren kok tak punya ijazah? Atau memang ada
sesuatu yang lain yang tersembunyi dalam kedalaman pikiran dan hati pak haji (mungkin
juga banyak orang) tentang hakikat ijazah? Apakah salaf bertolak punggung
dengan ijazah sehingga menjadi aturan yang tak boleh dilangkahi oleh pesantren?
Berangkat dari keremangan jawaban pertanyaan
tersebut tulisan ini dilahirkan. Bukan untuk memberikan jawaban, tapi
setidaknya menghadirkan titik renung yang diperlukan untuk masa depan. Apa yang
kita pahami sebagai sebuah pesantren barangkali perlu dicermati ulang, ke akar
sejarahnya, yang pada dasarnya ia merupakan hasil kontruksi sebuah kebudayaan Jawa.
Sebagai hasil kebudayaan, pesantren mengadopsi
nilai-nilai yang beragam, meskipun warna keislaman tampak lebih dominan.
Pesantren mirip dengan mandala yang menjadi tempat mempersiapkan
kader-kader kepemimpinan dalam tradisi Hindu dan Budha. Ia kemudian diadopsi oleh para
wali songo, dengan
terus mengalami metamorfosis dan modifikasi
ke titik yang lebih kompleks sampai sekarang. Karena muncul dari budaya
setempat, pesantren lebih akrab dengan masyarakat dari pada sistem pendidikan
lainnya, sekolah misalnya. Antara kiai, pengurus pesantren, santri dan
masyarakat sekitar membentuk ekosistem edukatif tersendiri yang sederhana,
membatin dan komprehensif.
Sementara di sisi lain, salaf merupakan sebuah
terma yang cukup memiliki definisi variatif. Ada yang menyebutnya sebagai ulama
yang hidup pada masa tiga abad pertama Islam. Ada pula yang merujuk pada
sebagian ulama yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat
mutasyabihat, juga lebih mengedepankan dalil naqli (al-Qur’an dan Hadits) dalam
menjelaskan ilmu kalam. Selanjutnya, salaf juga dipahami sebagai sesuatu yang
berbeda –bahkan bertolak belakang– dengan khalaf (modern), yang dalam catatan
sejarah, gerakan salafiyah ini dimotori oleh Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah,
muridnya, dan menemukan “kesempurnaannya” di tangan Muhammad Abdul Wahab (tokoh
pendiri madzhab Wahhabi yang pemikirannya cukup berpengaruh terhadap beberapa
gerakan Islam di Indonesia).
Lalu apa kaitannya dengan pesantren? Pesantren
jelas tidak memiliki hubungan yang sedarah dengan salaf ataupun khalaf. Kedua
terma tersebut lebih masuk pada persoalan epistimologis, warna pemikiran,
konsep nilai yang menjadi pilihan bebas setiap orang yang berkemungkinan
melakukannya. Namun demikian, sebutan pesantren salaf dan modern begitu semarak
dalam masyarakat, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Pesantren salaf lebih
menekankan pada pembelajaran kitab-kitab klasik (turats) tanpa sistem klasikal,
sementara pesantren modern lebih mengarah pada sistem belajar yang lebih
terbuka, sistematis dan biasanya berbasis teknologi. Walaupun kenyataan kadang
lebih kuat dari pada konsep dan ideologi yang digempar-gemporkan.
Ijazah Pesantren dan Kebohongan Angka
Tak ada pesantren yang tidak memiliki (baca: mengeluarkan)
ijazah bagi para santrinya. Akan tetapi, tata nilai yang dipakai dalam
mengeluarkan sebuah ijazah itu yang berbeda dengan, sebut saja misalnya,
sekolah. Di pesantren, seorang kiai
biasanya sudah mengerti betul santri-satrinya yang sudah dianggap lulus dan berhak melakukan dakwah di
masyarakat. Pengetahun sang kiai yang seperti ini merupakan ijazah awal bagi
seorang santri, yang ditandai dengan restu kiai, bahkan perintah langsung untuk
pulang dan melanjutkan tugas kanjeng Nabi dalam membangun umat.
Ijazah sama artinya dengan syahadah, kesaksian.
Para santri alumni pesantren, seain
dari kiai, mendapatkan ijazah atau kesaksian
langsung dari masyarakatnya. Masyarakat memiliki otoritas langsung dalam
menentukan siapa di antara insan pesantren yang lulus dari beragam ujian
kehidupan dan layak mendapat predikat “orang shaleh”. Ijazah itu tidak berupa
angka-angka dalam kertas, tapi pengakuan masyarakat setelah melihat langsung
“nilai manfaat” yang dimiliki para santri.
Tidak heran bila dalam sistem manajerial
pendidikan pesantren, bekerja merupakan bagian dari proses pembelajaran para
santri. Mereka tidak hanya mencari ilmu, tetapi membantu segala pekerjaan sang
kiai. Mengurus pertaniannya, peternakan, perkebunan, perawatan rumah, dan
segala pekerjaan lain yang dimiliki sang kiai beserta keluarga. Sehingga antara
ilmu dan amal (kerja) menjadi satu paket nilai yang tertanam dalam jiwa santri,
tidak terpisah sebagaimana ini dapat secara gamblang dilihat dalam sistem
formal pendidikan sekolah kebanyakan.
Apa yang diinginkan pak haji yang sedang risau
dalam memilih pesantren untuk anaknya sebenarnya bukan ijazah formal: sebuah
pengakuan di atas kertas yang diwakili angka-angka. Tetapi ijazah sejati yang
langsung diberikan masyarakat berupa sebutan “orang shaleh”. Hal ini wajar,
sebab sekolah selama ini mengejar target angka tertinggi untuk peserta
didiknya, dengan mengesampingkan sesuatu yang lebih penting. Para siswa dipaksa
untuk terus belajar dalam menghadapi ujian sekolah, bukan untuk menghadapi
“ujian sosial” yang justru berlangsung sepanjang hayat. Ah, jangan-jangan
semakin tinggi angka itu dalam ijazah, semakin tinggi pula tingkat
kebohongannya?.
Peara, Februari 2010
Peara, Februari 2010








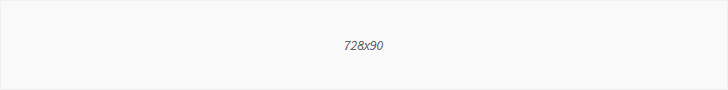








Tidak ada komentar:
Posting Komentar