Pendidikan adalah sesuatu yang tidak sama dengan
pendidikan yang diterima di sekolah (Postman, 2002). Pendidikan ibarat udara
yang hampir tidak memiliki bentuk yang pasti, tergantung pada ruang yang
ditempati. Namun demikian, ideologi pendidikan yang begitu beragam tidak bisa
secara serta merta dilaksanakan di mana saja, sebelum mengkritisinya lebih
lanjut dan menemukan formulasinya yang lebih tepat dan terarah, sesuai ruang
dan waktu.
Paulo Freire, salah satu tokoh pendidikan yang
memperkenalkan ideologi pendidikan kritis belakangan ini sangat digemari dan
digandrungi oleh beberapa tokoh, termasuk di negara kita. Persoalannya, apakah
pendidikan kritis versi Freire adalah benar-benar sebagai pendidikan alternatif
yang paling tepat? Bukankah ia juga merekonstruksi pemikirannya dari
tokoh-tokoh sebelumnya? Inilah sebuah catatan kecil yang ingin saya sampaikan :
Dunia yang Tampak
Sebagaimana diketahui secara umum bahwa filsafat Freire bertolak
dari kehidupan nyata (realitas material). Dunia dalam pandangan Freire
merupakan sarang penindasan yang terjadi melalui struktur kelas. Pendidikan
diarahkan pada upaya ktiris dalam menyingkap situasi penindasan yang
terselubung dan sistem ketidakadilan kelas. Dalam hal ini, kritisisme hanya
berhenti pada dual hal tersebut, yang keduanya merupakan fenomena material,
sebagaimana ini juga terlihat dalam sejarah pemikiran dan perjuangan kaum
marxis.
Padahal,
seharusnya pendidikan bisa merambah pada ranah yang lebih jauh,
immaterial-transendental, dengan menciptkan ruang kritis (baca: kecerdasan)
yang mampu menembus batas-batas budaya kemanusiaan yang profan. Sebab ukuran
kecerdasan, menurut falsafah nabi, adalah kesanggupan untuk selalu ingat kematian
dan pengendalian diri. Benar, segala bentuk penindasan dan ketidakadilan kelas
harus diselesaikan, akan tetapi bukan sebagai syarat pemenuhan kesejahteraan
kolektif, melainkan tugas kekhalifahan yang implikasi panjangnya dapat
ditemukan di akhirat, pasca kematian.
Berpikir
Bertindak; Juga Berdzikir
Paulo Freire
mengemas pendidikan kaum tertindasnya dalam konsep aksi dan refleksi.
Pendidikan yang hanya berputar-putar pada siklus berpikir dan bertindak secara
terus menerus dan berkesinambungan dalam sebuah lingkaran kesadaran yang tak
berujung. Model metodologi pendidikan seperti ini oleh Paulo Freire disebut
sebagai metode pendidikan hadap masalah (problem posing education).
Model
pendidikan tersebut tidak melibatkan “berdzikir” sebagai sebuah hal yang harus
terjadi dalam diri peserta didik. Padahal, ruang mental manusia yang manusiawi,
tidak bisa dipisahakan dari kemampuannya dalam berdzikir yang berjalan seimbang
dengan potensi berpikir dan beramal (bertindak). Berpikir adalah usaha dalam
menemukan ilmu, sedangkan berdzikir adalah upaya mendapatkan nilai. Ilmu dan
nilai adalah dua hal yang seharusnya mendorong dan melatarbelakangi setiap
tindakan (amal). Ilmu menuntun orang betindak secara profesional dan tidak
kontradiktif, tapi nilai memberikan ruang bertindak yang lebih bermanfaat dan
memantulkan kelembutan bagi diri, sesama dan lingkungan.
Guru yang
Murid, Murid yang Guru
Murid bukan
sebuah bejana kosong yang harus terus diisi oleh berbagai informasi
pengetahuan, tentunya oleh guru. Relasi guru-murid yang menempatkan murid
sebagai objek yang pasif, dalam pandangan Paulo Freire, adalah bagian dari
dehumanisasi yang hanya akan melahirkan manusia (meminjam istilah Erich From)
berwatak “nekrofili”, bukan “biofili”, yang hanya jadi pengagum status
quo dan penerus penindasan.
Guru tidak
selalu guru dan murid bukan senantiasa murid. Guru dan murid adalah sama-sama
subjek, saling bermitra, belajar dan sejajar, dalam memahami realitas hidup
sebagai objek pendidikan bersama. Implikasinya: murid bisa saja lebih tahu dari
guru, sehingga guru juga perlu belajar sama murid. Guru bisa menjadi murid,
murid bisa menjadi guru.
Selanjutnya
sudah bisa ditebak: guru tidak boleh (merasa) menjadi guru, tetapi harus
bersikap sebagai sahabat/mitra. Sebab idiom “guru” tidak steril dari aroma
penindasan, apalagi ketika guru harus benar-benar diproyeksikan sebagai sosok
yang digugu dan ditiru. Disinilah problematikanya: apakah murid juga harus
bersikap sebagai sahabat bagi gurunya?
Nabi memang
memperlakukan murid-muridnya sebagai sahabat, tetapi para murid tetap
memperlakukan nabi sebagai Nabi. Cara terbaik seorang guru ketika bersama
muridnya adalah dengan menjadikannya sahabat, dan cara terbaik seorang murid
ketika bersama gurunya dengan tetap menjadikannya sebagai guru. Ini tidak
mereduksi posisi kedua-duanya (guru-murid) sebagai subjek yang sejajar, seperti
yang diinginkan Paulo Freire, hanya sebagai paradigma dan etika bersikap yang
memang tidak mungkin harus disamakan. Yang terjadi hari ini, bukan hanya
persoalan guru yang salah dalam memperlakukan murid, tetapi juga perlakuan
murid yang tidak beretika kepada gurunya.
Epilog
Selebihnya,
apa yang dilakukan oleh Paulo Freire adalah sesuatu yang sangat berharga bagi
pendidikan, dan telah memberikan manfaat yang tidak ternilai. Gagasannya
tentang konsientisasi sebagai inti proses dan realitas diri dan dunia sebagai
hakikat tujuan pendidikan, sungguh telah memiliki andil yang besar terhadap
kehidupan masyarakat dan dunianya. Selain hal itu, sebagai seorang professor, ia
tidak terjebak di belakang meja dan menara gading, tapi langsung turun ke
lapangan menemani masyarakat kecil yang buta huruf untuk terus belajar
sepanjang hayat.
Namun, setiap
pemikiran adalah bayi yang baru lahir, dan kitalah yang harus merawat dan melengkapi
kebutuhannya agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan bermanfaat. Memahami
sebuah pemikiran adalah kesulitan tersendiri, dan merekonstruksi sebuah
pemikiran adalah sebuah kesulitan yang lain, yang lebih suit.










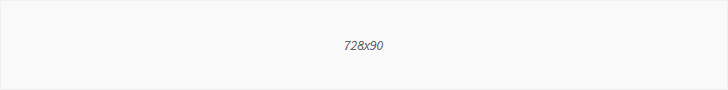







Tidak ada komentar:
Posting Komentar